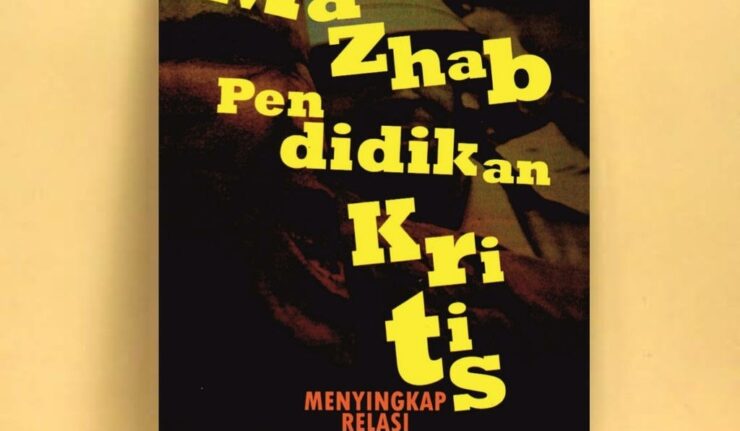Judul Buku : Mazhab Pendidikan Kritis
Penulis : Dr. M. Agus Nuryatno
Penerbit : Resist Book
Cetakan : Pertama, Mei 2011
Ketebalan Buku : 133 halaman
ISBN : 979-1097-88-8
Peresensi : Sulistia Muarifa
Berbicara soal pendidikan tidak pernah lepas dari konteks jajaran yang menaunginya. Sampai saat ini, pendidikan dianggap sebagai jalan menuju dunia kerja yang diinginkan. Ada yang beranggapan: semakin tinggi pendidikan semakin mapan pekerjaan yang didapat. Pandangan ini tak sepenuhnya salah. Hanya saja ketika pandangan simplisistik tersebut menjadi satu-satuya landasan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka lunturlah hakikat pendidikan untuk memanusiakan manusia.
Visi pendidikan kritis dilandaskan pada suatu pemahaman bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, kultur, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Institusi pendidikan tidaklah netral, independen, dan bebas dari berbagai kepentingan tapi justru menjadi bagian dari institusi sosial lain yang menjadi ajang pertarungan kepentingan. Pendidikan harus dipahami dalam kerangka relasi-relasi antara pengetahuan, kekuasaan dan ideologi. Dalam konteks di atas, perlu membangun kesadaran kritis peserta didik agar mereka mampu mengidentifikasi kepentingan ideologis yang menyelimuti realitas.
Jadilah pembelajaran sebagai arena imposisi pengetahuan dari mereka yang menganggap tahu segalanya kepada mereka yang tidak mengetahui apa-apa. Agus Nuryatno mengelaborasi tiga basis teori yang melandasi mazhab pendidikan kritis, Mazhab Frankfurt, Gramsci, dan Freire kaitannya dengan mobilitas sosial. Pendidikan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan yang berlangsung harus bersifat produktif, bukan reproduktif. Sayangnya, selama ini sekolah-sekolah masih berkutat pada aspek reproduktif. Sekolah-sekolah bermutu dan mahal melanggengkan dominasi kelompok yang kuat kapital atas kelompok tertindas dan lemah kapital. Pendidikan kritis menerangkan pada pembelajaran mengenai bagaimana memahami, mengritik dan mengubah realitas hidup dengan mengunakan ilmu pengetahuan dan perspektif.
Pendidikan kritis percaya bahwa sekolah memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan politik dan kultural. Sekolah tidak hanya mengenai penguasaan teknik dasar yang diperlukan masyarakat industri tetapi juga harus diorientasikan untuk menaruh perhatian pada isu-isu peningkatan harkat kemanusian dan menyiapkan manusia untuk hidup bersama di dunia. Pendidikan kritis berangkat dari kecintaan yang tinggi terhadap manusia. Siswa didik adalah manusia yang merdeka dan makhluk akatif bukan objek yang hanya beradaptasi dengan dunia.
Dalam pendidikan kritis, guru bukanlah segalanya dan satu-satunya sumber pengetahuan. Guru dan murid sama-sama belajar. Jika ilmu pengetahuan sepenuhnya hak prerogatif guru dan kebijakan pendidikan, teknik bottom up lebih diutamakan karena menjadi kehidupan peserta didik sebagai titik pijak sehingga teks yang dipelajari tidak jauh dari konteks tempat siswa didik hidup.
Dalam perspektif teori kritis, positivisme adalah bentuk baru yang paling efektif dari ideologi kapitalis dan mempunyai investasi dalam apa yang disebut Horkheimer (1985 dengan ‘’eclipse of reason‘’. George Friedmen (1981: 118 ) mengatakan ’’fungsi sosial dari ideologi positivisme adalah mendegradasikan fakultas akal yang kritis di bawah kekuasaan positivisme. Tidak dapat dihindarkan, akal berhenti aktifitasnya untuk mengritik. Gagasan tentang obyektifitas dalam tradisi positivisme telah menafikan arti penting kritik atas realitas. Menyangkut hubungan antara subyek dan obyek, manusia pada awalnya tampil sebagai subyek yang menciptakan dan mengontrol teknologi (obyek). Namun ketika obyek teknologi telah berkembang sedemikian rupa, posisinya berbalik; obyeklah yang justru mengontrol dan menguasai subyek. Di sinilah manusia telah terkontrol dan terdominasi oleh ciptaannya sendiri. Berbeda dengan Hegel yang mengembangkan konsep kritik berbasiskan pada filsafat idealisme, Marx mengembangkan konsep kritik dalam kerangka filsafat Materialisme. Menurut Marx, konsep Hegel tentang kritik masih kabur karena pemahamannya tentang sejarah masih abstrak.
Kapitalisme sebagai ideologi dominan saat ini punya pengaruh besar dalam setiap denyut nadi kehidupan manusia. Dominasi kapitalisme tidak hanya dalam wilayah ekonomi tapi telah merambah ke wilayah yang lain, termasuk di dalamnya dunia pendidikan. Dalam wilayah pendidikan, dampak yang paling nyata dari dominasi kapitalisme adalah pada salah satu produk yang dihasilkannya yaitu ”culture of positivism” (Giroux, 1983). Pengaruh kapitalisme dan budaya positivisme terhadap pendidikan sangat jelas yaitu ilmu yang mengorientasikan mereka untuk beradaptasi dengan dunia masyarakat industri dengan mengorbankan aspek critical subjectivity, yaitu kemampuan untuk melihat dunia secara kritis sedangkan pada mode of thought, yang dilahirkan oleh budaya positivisme adalah rasionalitas teknokratik (tecnocratic rationality) yang punya dua karakter utama: konformitas dan unit formitas.
Konformitas mengarahkan peserta didik untuk bersikap pasif dan adaptif terhadap teks (buku pelajaran) dan konteks (realitas kehidupan). Sikap pasif dan adaptif potensial untuk mendegradasi sikap kritis peserta didik. Sebab, teks dan konteks akan diterima apa adanya, tanpa reserve, dan tanpa kritik. Akibatnya, tidak ada dialektika ilmu pengetahuan. Knowledge production pun terjadi dalam satu arah.
Dalam bagian sebelumnya, telah dikemukakan bahwa pendidikan itu selalu bagaikan pedang bermata dua. Ia bisa dijadikan sebagai alat domestifikasi atau liberasi; sebagai media produksi atau reproduksi kelas sosial. Semuanya tergantung kepada siapa yang memaknai dan mempraktekkannya. Dalam perspektif mazhab pendidikan kritis, pendidikan dimaknai sebagai media mobilitas kelas sosial. Sekolah-sekolah bermutu dan mahal melanggengkan dominasi kelompok yang kuat kapital atas kelompok tertindas lemah kapital.
Sebenarnya buku ini sudah cukup menarik di awal, dilihat dari bagian awal yang sudah membahas mengenai konsep-konsep dasar pendidikan. Tentunya, pembaca akan mendapatkan wawasan sederhana dulu sebelum mendapatkan pengetahuan yang lebih kompleks. Bagi pembaca, judul buku ini sangat menarik untuk didalami. Cover yang didesain cukup membuat pembaca mengerti apa isi yang termuat di dalamnya. Buku ini memberikan pandangan mengenai pendidikan serta isu-isu yang dibagi dalam 4 bab. Bahasa yang digunakan untuk pembaca yang masih awam akan cukup menguras pemahaman namun istilah-istilah ini mampu memberikan banyak wawasan. Berbagai pandangan yang disajikan dalam buku, membuat pembaca, tentunya jika yang membaca adalah seorang pendidik atau yang berkecimpung dalam dunia pendidikan sangat recommended dengan isi yang menonjok bahwa mendidik adalah bentuk representasi dalam kehidupan.