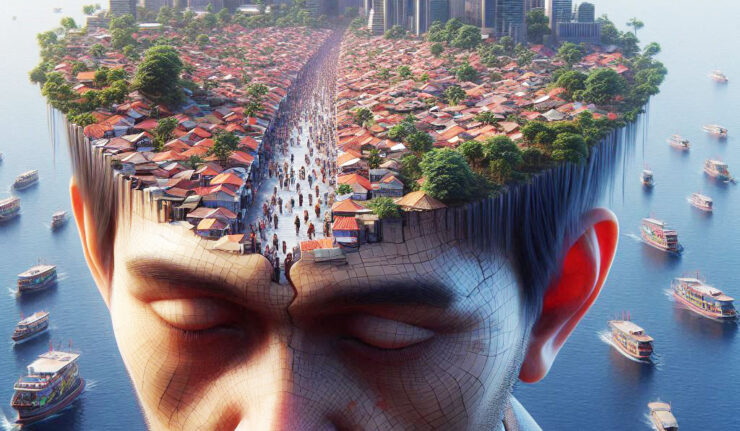Sekira lebih dari sebulan lalu, penulis berjumpa seorang kawan pimpinan Partai Buruh. Di pertemuan ini penulis menangkap kegelisahannya atas keadaan berdemokrasi atau lebih khususnya sistem politik yang berlaku. Pengalaman empirik memberi pelajaran yang kaya. Dari sudut pandang sesama ‘orang partai’, kami paham tidak mudah membangun partai politik, tidak mudah menjadikan partai politik sebagai peserta pemilu, dan tidak mudah memperoleh dukungan dalam kompetisi. Kami mengerti bagaimana preferensi pilihan rakyat ditentukan oleh beragam hal dan kompensasi ekonomi jangka pendek tetap berperan sangat besar meski tidak mutlak.
Keunikan dari keadaan-keadaan dan para pelaku dalam transformasi politik selama dua setengah dekade, dari kediktatoran menuju liberal, mungkin dapat menjadi suatu kajian tersendiri oleh para pundit politik. Namun alas dari perjalanan ruang dan waktu itu yang paling penting untuk dirumuskan dan disimpulkan.
Perubahan dari sistem politik kediktatoran ke liberal sesungguhnya mencerminkan perubahan pada realitas ekonomi. Dorongan liberalisasi sejak 1980-an mencapai puncaknya di tahun 1997-1998 yang memaksa terjadinya reformasi politik. Penyediaan ekosistem bagi deregulasi, penghapusan subsidi, dan privatisasi berhasil dituntaskan hingga akhir periode pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Sampai pada titik tersebut, ternyata ada arus balik yang mendorong terjadinya de-liberalisasi. Meski diiringi kritik atas polarisasi ekonomi antara oligarki dan rakyat biasa, dalam pemerintahan Jokowi peran negara di banyak bidang ekonomi mengalami peningkatan. Pembangunan infrastruktur, proyek lumbung pangan, dan hilirisasi adalah contoh yang paling jelas dilihat. Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, menyatakan “peran negara” ini sebagai sistem ekonomi Pancasila. Ia menjelaskan bahwa sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem campuran dengan “mengambil hal-hal baik dari kapitalisme dan hal-hal baik dari sosialisme”. Adanya peran atau campur tangan negara dalam mengatur perekonomian merupakan salah satu ciri dari ekonomi sosialis.
Bila kita kesampingkan sementara diskusi tentang hal-hal baik apa saja dari kedua -isme tersebut, kita temukan esensi yang mengkonfirmasi bahwa de-liberalisasi memang sedang terjadi. Konfirmasi ini tak lain turut didorong oleh perkembangan geopolitik dunia yang sedang bergeser sehingga nilai-nilainya pun bergeser. Kapitalisme liberal dengan nama neoliberalisme itu sudah tergerus dan ditinggalkan oleh banyak pemerintahan. Sejumlah kalangan kemudian memperkenalkan istilah iliberal sebagai lawan dari demokrasi liberal. Introduksi yang dikotomis ini tidak sepenuhnya tepat ketika iliberal dimaknai pembatasan untuk kebebasan berpikir dan berperilaku. Padahal alternatif terhadap demokrasi liberal jauh lebih luas dari itu.
Doktrin tentang kesakralan pasar tanpa campur tangan negara tak lagi laku. Banyak kalangan, dari akademisi hingga politisi, sudah sampai pada kesimpulan bahwa sistem neoliberalisme hanya menguntungkan sedikit elit dunia terutama segelintir kapitalis finance di Wall Street, Amerika Serikat. Bagi Indonesia, ditambah segelintir konglomerat yang menikmati laba super besar dari sektor ekstraktif.
Di tahun 1980, ketika Deng Xiaoping meninjau kembali pemahaman Tiongkok dalam usaha mencapai tatanan sosialisme, ia sampai pada kesimpulan bahwa revolusi bukan semata soal perjuangan kelas melainkan juga usaha untuk memajukan tenaga produktif. Bahkan Deng katakan, pemajuan tenaga produktif itu merupakan hal paling fundamental dalam revolusi bila dilihat dari sudut pandang sejarah perkembangan masyarakat. Dasar pemikiran itu tidak akan menjadi apa-apa tanpa penerjemahan yang berkelanjutan di pemerintahan Tiongkok setelah Deng Xiaoping. Tapi setelah empat dekade kita mengenal Tiongkok sebagai negara dengan perkembangan tenaga produktif paling cepat dibandingkan negara-negara lain di dunia. Tiongkok memanfaatkan celah-celah dalam sistem kapitalisme untuk merangsang serta menyerap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sebuah kepemimpinan politik yang berkepastian dan berkelanjutan.
Di sinilah letak salah satu kendala penting sistem demokrasi liberal yaitu keberlanjutan. Apapun hal strategis yang sudah diletakkan fondasinya untuk bangunan ekonomi-politik yang lebih adil dan menyejahterakan rakyat harus dilanjutkan. Sementara demokrasi liberal tidak bisa menjamin keberlanjutan itu. Keberadaan regulasi seperti Undang-Undangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dapat dengan mudah disabotase dengan menerbitkan Undang-Undang lain yang bertentangan dengan rencana tersebut.
Pandangan yang parsial dan sempit telah mengarahkan keriuhan politik belakangan ini sebagai persoalan individu atau keluarga Presiden Joko Widodo. Berbagai atribusi negatif yang disematkan kepada Presiden Jokowi meskipun tanpa fakta hukum atau berbasis analisa dan asumsi belaka. Terlepas bagaimana peran Presiden Jokowi, gejala yang disebut sebagai “kemunduran berdemokrasi” hanya dapat dipahami dengan menyertakan potret situasi yang lebih komprehensif. Garis-garis besar kesimpulan atas situasi tersebut coba penulis diuraikan sebagai berikut.
Pertama, keberlanjutan intervensi negara yang lebih besar dalam bidang ekonomi mensyaratkan keberadaan institusi kekuasaan yang lebih kuat dan mapan. Program strategis seperti hilirisasi (dengan perspektif industrialisasi), keadulatan energi, dan lumbung pangan (food estate) tidak mungkin dijalankan oleh suatu rezim liberal. Tidak pernah ada contoh sejarah negara manapun di dunia yang sukses melakukan industrialisasi tanpa pemerintahan yang kuat, yang juga melakukan pembatasan terhadap hal-hal yang berlaku dalam demokrasi liberal. Jepang dengan rezim Meiji, Korea Selatan dengan kediktatoran militer, Singapura dengan police state, hingga China dengan kepemimpinan Partai Komunis. Negara-negara Barat sekalipun pada tahap awal industrialisasinya di abad ke-19 menerapkan pemerintahan yang otoritarian. Setelah industrinya mapan baru mereka menerapkan demokrasi liberal.
Kedua, kecenderungan untuk mulai meninggalkan liberalisme politik ini menyisakan persoalan dominasi elit ekonomi tertentu terhadap kekayaan negara. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam derajat tertentu telah mewakili keresahan ini. Hingga sekarang Prabowo masih konsisten dengan kesimpulan pembacaannya tentang “mengalirnya kekayaan nasional ke luar” (net outflow of national wealth). Kita berharap, dan harus kita kawal, bahwa dalam pemerintahannya pasca 20 Oktober 2024 nanti langkah-langkah konkret untuk membatasi yang kuat dan mengafirmasi yang lemah akan segera dilakukan. Penulis pribadi berpendapat pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah-langkah intervensi negara yang lebih besar ke dalam perekonomian nasional dibandingkan pemerintahan Jokowi.
Ketiga, ternyata bangsa ini tidak punya cukup modal budaya untuk menjalankan demokrasi liberal yang pada hakikatnya berpijak pada kemerdekaan individu dan pada praktiknya hanya menguntungkan segelintir oligarki. Premis Francis Fukuyama tentang otonomi individu terhadap kekuasaan ternyata tidak tercermin dalam salah satu prosedur dasar demokrasi liberal yaitu pemilu. Pembatasan-pembatasan terhadap partisipasi rakyat, dengan menyisakan sedikit elit yang terkonsolidasi, justru menjadi ciri dari praktik demokrasi liberal di Indonesia. Ketika sejumlah pihak ramai mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran etik dan prosedur dalam berdemokrasi (dalam makna liberal), pihak-pihak tersebut seakan lupa bahwa wujud demokrasi yang eksis sekarang tidak pernah didiskusikan secara mendalam. Amien Rais sendiri, sebagai orang yang paling bertanggungjawab terhadap amandemen karena posisinya Ketua MPR kala itu, menyatakan penyesalan dan permintaan maaf atas amandemen yang terjadi. Penulis tidak mengidolakan seorang Amien Rais, tapi pengakuan dan permintaan maaf tersebut kiranya patut dipertimbangkan.
Sebagaimana makluk hidup menyesuaikan dirinya terhadap perubahan alam, aturan-aturan pun menyesuaikan relevansinya terhadap perkembangan zaman. Kita tidak lagi berada di zaman demokrasi liberal dipuja sebagai nilai dengan keluhuran tertinggi dalam peradaban. Nilai itu mungkin cocok bagi negara bangsa tertentu dalam waktu tertentu, tapi terbukti tidak cocok bagi banyak negara bangsa lain. Pemaknaan terhadap demokrasi ternyata harus digelar kembali.
Sejalan dengan kehendak untuk memaksimalkan peran negara dalam perekonomian, ruang bagi partisipasi politik rakyat harus dibuka selebar-lebarnya. Perlu ditemukan mekanisme berdemokrasi yang memungkinkan partisipasi tersebut. Misalnya, setiap draft keputusan strategis harus disampaikan kepada rakyat melalui struktur pemerintahan untuk memperoleh pendapat dan masukan sebelum dijalankan. Dengan keterlibatan tersebut maka legitimasi dan dukungan rakyat terhadap setiap program pemerintah akan menjadi lebih paripurna sehingga pada gilirannya akan memperkuat pemerintahan.
Indonesia pernah punya Demokrasi Terpimpin pada 1959-1967 dengan kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya “demokrasi terpimpin” ini seolah diadopsi Orde Baru, tapi dengan menyingkirkan kekuatan Kiri yang merupakan salah satu fondasi ideologis lahirnya Republik Indonesia. Konsolidasi kapital asing, birokrat, militer, teknokrat dan kapitalis kroni merupakan pilar bagi Orde Baru di atas ideologi pembangunanisme. Pada gilirannya kapital asing menuntut liberalisasi total yang menumbangkan rezim itu. Demokrasi tanpa fondasi kerakyatan terbukti rapuh. Demokrasi liberal sesungguhnya menyerahkan kepemimpinan kepada pasar atau kapital, sehingga juga rapuh.
Filosofi demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila adalah “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Rumusan frasa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” menunjukkan bahwa demokrasi kita adalah “demokrasi terpimpin”. Kepemimpinan “hikmat kebijaksanaan” tersebut teraktualisasikan pada hasil pemikiran para pemimpin berupa visi, misi dan program pemerintahan. Artinya, kepemimpinan itu bukan soal orang atau tokoh melainkan kepemimpinan konsepsi yang lahir dari akal-budi.
Dalam puluhan tahun pelaksanaannya, hal yang hilang dari prinsip di atas adalah paradigma Kerakyatan, sehingga makna subyek dan orientasi pada rakyat selalu dengan mudah dimanipulasi dan diselewengkan. Kita boleh punya pemikiran dan konsep-konsep yang hebat, tapi ketika hanya menempatkan rakyat sebagai obyek maka sejarah kerapuhan sedang berulang. Sudah tiba momentum untuk meninjau dan mengubah paradigma dan konsep berdemokrasi kita. Tinggalkan demokrasi liberal, buka kesempatan untuk menerapkan demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
Penulis: Dominggus Oktavianus (Sekjend PRIMA)